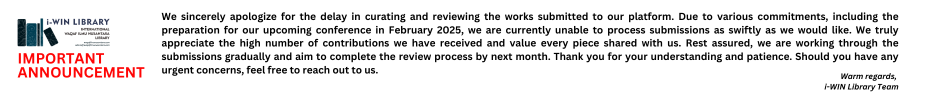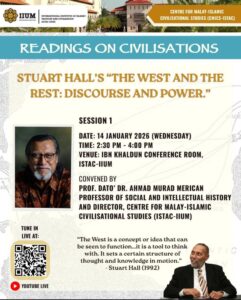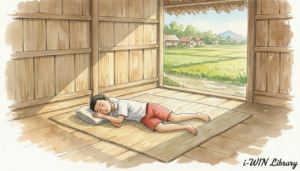FINALITAS VS KONTROL YUDISIAL: HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DAN PTUN (STUDI KASUS PKPI 2019)
Artikel ini membahas ketegangan antara prinsip finalitas administratif dan kontrol yudisial dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, dengan fokus pada kasus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tahun 2019. Melalui analisis hukum mendalam, penulis menguraikan bagaimana putusan Bawaslu yang bersifat non-final membuka ruang bagi PTUN untuk melakukan kontrol yudisial terhadap keputusan KPU. Kondisi ini menimbulkan dilema antara efisiensi penyelenggaraan pemilu dan perlindungan hak konstitusional peserta pemilu. Artikel ini menegaskan perlunya rekonstruksi norma agar hubungan kewenangan antara Bawaslu dan PTUN menjadi lebih harmonis dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia.
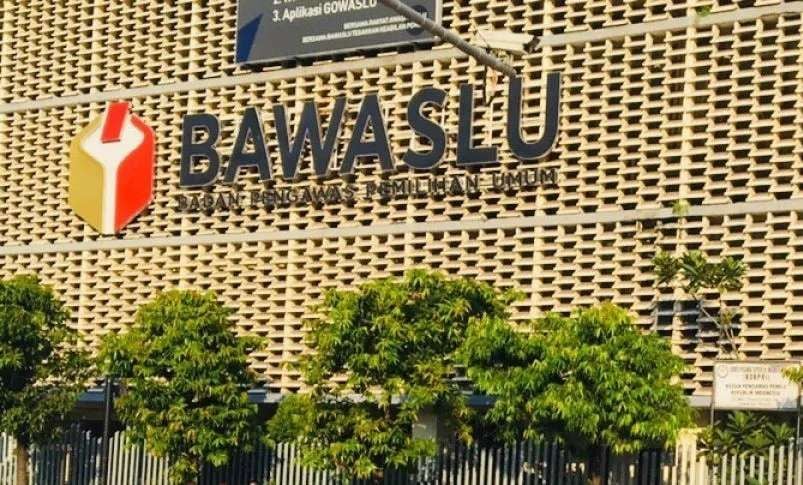
LATAR BELAKANG
Dalam sistem demokrasi elektoral, kepastian hukum merupakan pilar utama yang menjamin terselenggaranya pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Prinsip ini berfungsi menjaga stabilitas penyelenggaraan pemilu sekaligus melindungi hak politik warga negara dari tindakan administratif yang sewenang-wenang. Menurut Philipus M. Hadjon, kepastian hukum merupakan bagian integral dari asas legalitas yang menuntut setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada norma hukum yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.[1] Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu, asas ini menuntut agar setiap keputusan lembaga penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum yang jelas dan tetap terbuka terhadap mekanisme kontrol hukum yang objektif.
Secara normatif, mekanisme penyelesaian sengketa proses penetapan partai politik peserta pemilu diatur dalam Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menegaskan bahwa sengketa antara partai politik dan KPU diselesaikan terlebih dahulu melalui Bawaslu. Tahapan di Bawaslu merupakan upaya administratif wajib (mandatory administrative remedy) yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun demikian, dalam perkara ini secara dikecualikan putusan bawaslu tidak memiliki kekuatan final dan mengikat (final and binding), sehingga putusannya merupakan syarat formil semata untuk memastikan bahwa upaya administratif telah dilaksanakan, sedangkan objek sengketa yang sesungguhnya adalah keputusan KPU yang menimbulkan akibat hukum konkret bagi partai politik.
Namun dalam praktiknya, perdebatan muncul ketika putusan PTUN berpotensi berbeda atau bahkan bertentangan dengan putusan Bawaslu, sebagaimana terlihat dalam Kasus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tahun 2019. Dalam kasus tersebut, Bawaslu menolak permohonan PKPI terhadap keputusan KPU, tetapi PTUN DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT justru mengabulkan gugatan PKPI dan memerintahkan KPU untuk menetapkannya sebagai peserta Pemilu 2019. Situasi ini menimbulkan perdebatan di ruang publik, sebagian pihak menilai langkah PTUN sebagai bentuk penegakan hukum yang menjamin hak konstitusional partai politik, sementara sebagian lainnya menganggapnya berpotensi mengganggu kepastian dan efisiensi tahapan pemilu.
Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, supremasi hukum dalam negara hukum (rechtstaat) hanya dapat terwujud apabila tidak ada satu pun tindakan pemerintahan yang berada di luar jangkauan mekanisme pengawasan hukum.[2] Oleh karena itu, menutup kemungkinan uji yudisial terhadap keputusan administratif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip rule of law dan hak atas keadilan substantif (the right to a fair trial). Dengan demikian, kejelasan relasi kewenangan antara Bawaslu dan PTUN perlu ditegaskan agar penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga memenuhi rasa keadilan publik dan prinsip negara hukum yang demokratis.
KASUS POSISI
Kasus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada Pemilu 2019 merupakan preseden penting dalam hubungan kewenangan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Permasalahan bermula ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan hasil verifikasi faktual, menyatakan bahwa PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 karena tidak lolos verifikasi keanggotaan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Keputusan ini memiliki akibat hukum langsung terhadap hak PKPI untuk mengikuti kontestasi elektoral nasional.
Tidak menerima hasil tersebut, PKPI mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu, dengan dalil bahwa KPU telah melakukan kesalahan prosedural dan tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi partai untuk memperbaiki hasil verifikasi faktual. Permohonan ini diajukan berdasarkan Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses antara partai politik peserta pemilu dan KPU. Dalam konteks ini, Pasal 469 ayat (1) secara eksplisit mengatur bahwa putusan Bawaslu terhadap sengketa proses pendaftaran partai politik peserta pemilu tidak bersifat mengikat. Dengan demikian, putusan Bawaslu hanya merupakan upaya administratif, atau syarat formil yang harus ditempuh sebelum sengketa diajukan ke ranah peradilan tata usaha negara.
Dalam perkara PKPI, Bawaslu menolak permohonan yang diajukan dengan alasan bahwa KPU telah melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, karena sifat putusan Bawaslu dalam konteks Pasal 469 tidak bersifat mengikat, PKPI tetap berhak menempuh jalur hukum berikutnya. PKPI kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, dengan mendalilkan bahwa keputusan KPU termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, yang oleh karenanya dapat diuji secara yudisial.
Dalam Putusan PTUN DKI Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, majelis hakim berpendapat bahwa keputusan KPU terkait tidak diloloskannya PKPI sebagai peserta Pemilu adalah keputusan administratif yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi PKPI. Dengan demikian, keputusan tersebut termasuk objek sengketa tata usaha negara yang sah untuk diuji. PTUN akhirnya mengabulkan gugatan PKPI dan memerintahkan KPU untuk menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.
Pertentangan muncul karena Bawaslu sebelumnya telah menolak sengketa PKPI, sementara PTUN justru memutus sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan konflik interpretasi terhadap batas finalitas putusan Bawaslu dan kewenangan kontrol yudisial PTUN. Menurut Ridwan HR, finalitas administratif hanya berlaku dalam ranah internal pemerintahan, sedangkan tindakan administratif yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap warga negara tetap tunduk pada pengawasan yudisial (judicial review) untuk menjamin asas legalitas (rechtmatigheid).[3] Dengan demikian, putusan Bawaslu dalam konteks Pasal 469 tidak dapat dianggap mengikat secara yudisial, dan PTUN berwenang mengoreksi atau membatalkan keputusan administratif yang melanggar prinsip hukum atau hak warga negara.
ANALISA HUKUM
Identifikasi Dasar Hukum
- UUD 1945
- Pasal 1 ayat (3): Menegaskan Indonesia sebagai negara hukum (rule of law).
- Pasal 24 ayat (1): Kekuasaan kehakiman bersifat independen untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- Pasal 28D ayat (1): Menjamin setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Pasal 93: Menetapkan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.
- Pasal 466-468: Mengatur mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu.
- Pasal 469 Ayat (1): Menegaskan pengecualian bahwa berkaitan dengan sengketa verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Putusan Bawaslu tidak bersifat final dan mengikat.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009
- Pasal 1 angka 9: Menjelaskan definisi keputusan tata usaha negara (KTUN).
- Pasal 47-53: Memberikan kewenangan PTUN untuk menguji dan membatalkan keputusan administratif yang melanggar hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017
- Mengatur tata cara pengajuan sengketa proses pemilu di PTUN setelah upaya administratif di Bawaslu ditempuh.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Pasal 10 dan 53: Menegaskan asas legalitas, akuntabilitas, serta hak warga negara untuk menggugat keputusan pemerintahan yang melanggar hukum.
- Putusan Terkait
- PTUN DKI Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT (Kasus PKPI 2019).
Kewenangan Bawaslu sebagai Badan Quasi-Yudisial dan Sifat Dilematis Finalitas Putusannya
Dalam kerangka hukum kepemiluan, Bawaslu memegang peran strategis sebagai auxiliary state organ yang menggabungkan fungsi administratif dan fungsi adjudikatif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan/atau merekomendasikan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kewenangan ini menunjukkan bahwa Bawaslu beroperasi dalam posisi yang unik – ia bukan lembaga yudisial dalam arti formil, tetapi memiliki peran adjudikatif dalam ranah administratif.
Dalam konteks ini, sifat final dan mengikat sebagaimana termuat dalam Pasal 470 ayat (1) UU Pemilu sebenarnya harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan Pasal 469 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, yang membedakan antara sengketa proses pemilu yang melibatkan keputusan KPU dan sengketa yang berkaitan dengan tahapan lain. Dalam perkara PKPI 2019, putusan Bawaslu tidak memiliki daya ikat substantif terhadap KPU karena objek sengketanya adalah keputusan administratif KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, sifat “final dan mengikat” putusan Bawaslu dalam perkara tersebut bersifat administratif-prosedural formil, bukan substantif-yuridis.
Artinya, putusan Bawaslu berfungsi sebagai syarat administratif awal (preliminary procedural step) sebelum sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tahapan ini mencerminkan mekanisme internal check dalam sistem penyelenggaraan pemilu, di mana Bawaslu berperan sebagai filter atau pengawas awal terhadap tindakan KPU. Namun demikian, karena Bawaslu bukan lembaga peradilan, keputusan yang dihasilkannya tetap terbuka untuk diuji oleh PTUN, terutama apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik atau penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).[4]
Di sinilah muncul sifat dilematis dari posisi putusan Bawaslu. Di satu sisi, Bawaslu dituntut untuk memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, final, dan memberikan kepastian dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, finalitas administratif tersebut tidak dapat menyingkirkan hak konstitusional peserta pemilu untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan.[5] Akibatnya, dalam praktik seperti kasus PKPI 2019, putusan Bawaslu yang bersifat administratif-prosedural dapat berbeda bahkan berlawanan dengan putusan PTUN DKI Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, yang menilai aspek legalitas dan keabsahan keputusan KPU secara substantif.
Perbedaan hasil putusan ini menimbulkan problematika serius dalam tataran norma dan praktik. Pertama, menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum (legal certainty), karena dua lembaga negara dapat menghasilkan dua putusan berbeda atas objek permasalahan yang sama. Kedua, secara sistemik, hal ini menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan internal terhadap KPU, kewenangannya dalam penyelesaian sengketa proses belum mencapai tingkat finalitas yuridis yang dapat mencegah tumpang tindih kewenangan dengan PTUN.
Dengan demikian, posisi Bawaslu menjadi ambivalen dan dilematis: di satu sisi ia merupakan pengawas internal yang bertugas memastikan kepatuhan prosedural penyelenggara pemilu, namun di sisi lain tidak memiliki otoritas hukum yang cukup kuat untuk menjadikan keputusannya dalam perkara ini sebagai final and binding decision dalam arti substantif. Dalam tataran sistem hukum administrasi, putusan Bawaslu lebih tepat dipahami sebagai putusan administratif yang berfungsi memperkuat mekanisme akuntabilitas internal penyelenggaraan pemilu, bukan sebagai putusan peradilan yang menutup ruang bagi pengujian yudisial. Oleh karenanya, PTUN tetap memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan tindakan KPU, sehingga peran Bawaslu lebih bersifat preventive supervisory mechanism ketimbang adjudikatif absolut.
Peran PTUN dalam Pengawasan Legalitas
Dalam kerangka hukum administrasi, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi utama sebagai judicial control mechanism terhadap setiap tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam konteks pemilu, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan penetapan partai politik peserta pemilu merupakan bentuk KTUN karena memenuhi unsur konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan.
Kewenangan PTUN menjadi signifikan ketika keputusan KPU yang dijadikan objek sengketa telah melewati proses administratif di Bawaslu. Dalam perkara PKPI tahun 2019, Bawaslu menolak permohonan sengketa proses terhadap KPU, dan keputusan tersebut dianggap sebagai langkah administratif-prosedural untuk membuka ruang upaya hukum berikutnya. Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan pengecualian sifat final dan mengikat putusan bawaslu dalam perkara sengketa penetapan partai politik peserta pemilu, sehingga putusannya hanya bersifat administratif-prosedural, bukan substantif-yuridis. Artinya, Bawaslu hanya menilai aspek kepatuhan terhadap prosedur dan tahapan pemilu, bukan pada keabsahan hukum atau legalitas substantif dari keputusan KPU. Dengan demikian, ketika putusan Bawaslu hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian administratif awal, maka PTUN tetap memiliki kompetensi absolut untuk menguji legalitas keputusan KPU dalam rangka menjamin perlindungan hukum konstitusional.
Posisi ini menunjukkan adanya potensi perbedaan antara hasil putusan Bawaslu dan PTUN. PTUN tidak terikat secara yuridis pada putusan Bawaslu, karena objek sengketanya berbeda: PTUN mengadili keabsahan keputusan KPU sebagai badan administrasi negara, sedangkan Bawaslu menilai sengketa antar peserta pemilu pada ranah prosedural. Dengan demikian, apabila PTUN memutus berbeda dari Bawaslu, hal tersebut tidak menimbulkan conflict of authority, melainkan mencerminkan fungsi kontrol yudisial dalam memastikan asas rechtmatigheid (keabsahan hukum) dan doelmatigheid (kepatuhan terhadap tujuan hukum). Mengutip pandangan Paulus Effendie Lotulung, pengawasan yudisial oleh PTUN merupakan upaya menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga administrasi publik.[6] Oleh karenanya, hubungan antara Bawaslu dan PTUN bersifat komplementer dalam kerangka checks and balances hukum administrasi negara – Bawaslu berfungsi menjaga ketertiban prosedural pemilu, sementara PTUN memastikan keabsahan substantif keputusan KPU sebagai manifestasi prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara
OPINI HUKUM
Secara normatif, kerangka hukum kepemiluan Indonesia menghendaki keseimbangan antara efisiensi administratif dan keadilan substantif. Namun dalam praktiknya, keseimbangan ini menjadi rapuh ketika dihadapkan pada perkara sengketa proses pemilu yang objeknya adalah keputusan KPU karena Pasal 469 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit menyatakan bahwa putusan Bawaslu dalam perkara ini tidak bersifat final dan mengikat. Konsekuensinya, posisi Bawaslu sebagai lembaga quasi-yudisial menjadi dilematis dan cenderung kehilangan daya finalitas hukum yang kuat, meskipun secara fungsi ia diharapkan menjaga integritas prosedural penyelenggaraan pemilu.
Dilema ini muncul karena secara normatif Bawaslu bertugas mengawal proseduralitas dan kepatuhan administratif dalam penyelenggaraan pemilu, namun secara substantif keputusannya tidak mampu menutup ruang koreksi yudisial oleh PTUN. Dalam hal ini, putusan Bawaslu hanya memiliki daya mengikat administratif-prosedural (formil), bukan substantif-yuridis. Padahal, idealnya lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dapat memberikan kepastian hukum yang relatif cepat dan final dalam setiap tahapan pemilu. Ketika sifat finalitasnya tidak diakui secara substantif, hasil pengawasan dan penyelesaiannya menjadi rawan “dibatalkan” oleh pengujian yudisial di PTUN, sebagaimana terjadi dalam putusan PTUN DKI Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT.
Dalam perspektif hukum administrasi, keadaan ini menimbulkan dilema sistemik. Di satu sisi, pengawasan oleh Bawaslu merupakan bentuk self-correcting mechanism yang diatur secara internal dalam sistem kepemiluan, bertujuan untuk menghindari intervensi berlebihan dari lembaga peradilan umum agar tahapan pemilu tetap efisien dan tepat waktu. Namun di sisi lain, hak atas perlindungan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) membuka ruang legitimasi bagi PTUN untuk tetap dapat memeriksa keabsahan keputusan administratif KPU. Akibatnya, meskipun secara politik Bawaslu diharapkan menjadi “pengadil pertama” dalam sengketa proses pemilu, secara yuridis ia tidak dapat memberikan penetapan penilaian keabsahan hukum keputusan KPU.
Dilema ini semakin tajam ketika dua lembaga, yaitu Bawaslu dan PTUN, berpotensi mengeluarkan putusan yang berbeda atas objek yang secara substansi sama. Dari perspektif kepastian hukum, hal ini berpotensi menimbulkan legal uncertainty dan persepsi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Namun jika ditarik ke ranah rule of law, perbedaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari pembagian fungsi kontrol administratif dan yudisial dalam sistem checks and balances. Dengan demikian, persoalannya bukan semata pada konflik kewenangan, melainkan pada desain hukum yang belum menempatkan Bawaslu dalam posisi adjudikatif yang berdaya mengikat secara substantif.
Dengan kata lain, putusan Bawaslu yang hanya bersifat administratif-prosedural justru menempatkannya pada posisi rentan. Ketika Bawaslu berupaya menjaga idealitas prosedural penyelenggaraan pemilu, putusannya tetap dapat “dikesampingkan” oleh PTUN atas dasar pertimbangan keabsahan hukum yang lebih mendalam. Situasi ini menunjukkan adanya asimetri otoritas yuridis antara Bawaslu dan PTUN dimana Bawaslu memutus demi efektivitas tahapan pemilu, sedangkan PTUN menilai demi kepatuhan terhadap prinsip legalitas dan perlindungan konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, sistem yang ada saat ini menempatkan Bawaslu dalam posisi dilematis antara efektivitas administratif dan supremasi hukum substantif.
KESIMPULAN
Hubungan kewenangan antara Bawaslu dan PTUN dalam penyelesaian sengketa proses penetapan partai politik peserta pemilu, sebagaimana tergambar dalam kasus PKPI 2019, memperlihatkan ketegangan inheren antara prinsip finalitas administratif dan kontrol yudisial. Sifat putusan Bawaslu yang berdasarkan Pasal 469 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak bersifat final dan mengikat menyebabkan lembaga ini hanya berperan sebagai pengawas prosedural, bukan penentu legalitas substantif. Akibatnya, meskipun Bawaslu berfungsi menjaga integritas dan efisiensi tahapan pemilu, keputusannya tetap terbuka untuk diuji secara yudisial di PTUN. Ketika PTUN kemudian memutus berbeda, seperti dalam kasus PKPI, memunculkan dilema sistemik antara kebutuhan akan kepastian dan efektivitas penyelenggaraan pemilu dengan kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi peserta pemilu.
Dengan demikian, problematika ini bukan sekadar soal tumpang tindih kewenangan, tetapi lebih pada ketidakseimbangan desain normatif antara fungsi pengawasan administratif dan fungsi pengujian yudisial. Posisi Bawaslu menjadi ambivalen karena di satu sisi dituntut menghasilkan putusan yang cepat dan pasti demi menjaga tahapan pemilu, namun di sisi lain tidak memiliki kekuatan yuridis substantif yang dapat menutup ruang koreksi oleh PTUN. Oleh karenanya, perlu ada rekonstruksi norma yang mempertegas batas finalitas administratif Bawaslu sekaligus mengharmonisasi relasinya dengan PTUN agar mekanisme penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga menjamin keadilan hukum dan kepastian konstitusional dalam sistem pemilu yang demokratis.
DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. Peradilan etik dan etika konstitusi: perspektif baru tentang “rule of law and rule of ethics” & “constitutional law and constitutional ethics.” Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Hadjon, Philipus M. Pengantar hukum administrasi Indonesia. Cetakan kesebelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
Hadjon, Philipus M. “PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO. 30 TH. 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.” Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 1 (Maret 2015): 51. https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64.
Illahi, Beni Kurnia, Ikhbal Gusri, dan Gianinda A Sugiato. Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi. 1, no. 2 (2021).
Ridwan, H. R. Hukum administrasi negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Suciara, Angelica, Bryan Idias, Nathasya Jhonray Siregar, Tasya Amira Frananda Siregar, dan Tri Widyasto Prabowo. Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, Dkpp Dan Ptun Dalam Sengketa Pilkada Dan Implikasinya Terhadap Hukum. t.t.
[1] Philipus M. Hadjon, Pengantar hukum administrasi Indonesia, Cetakan kesebelas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
[2] Jimly Asshiddiqie, Peradilan etik dan etika konstitusi: perspektif baru tentang “rule of law and rule of ethics” & “constitutional law and constitutional ethics,” Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
[3] H. R. Ridwan, Hukum administrasi negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
[4] Ridwan, Hukum administrasi negara.
[5] Asshiddiqie, Peradilan etik dan etika konstitusi.
[6] Philipus M Hadjon, “PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO. 30 TH. 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,” Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 1 (Maret 2015): 51, https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64.