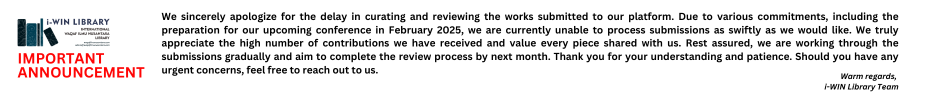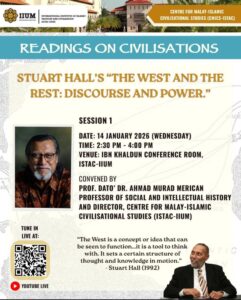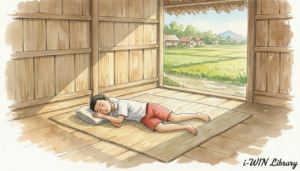KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL
Penjabaran kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerintahan sebagai institusi hukum yang tertib. Karena itu, produk-produk hukum yang dihasilkan selain mencerminkan prinsip ketuhanan yang maha esa, juga haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.
Negara hukum modern menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Prinsip popular sovereignty ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan tidak berasal dari kehendak pribadi penguasa, melainkan dari rakyat yang secara kolektif menyerahkan kewenangannya kepada negara melalui suatu kontrak sosial. Dalam konteks Indonesia, kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Namun, kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari hak-hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional merupakan hak yang diatur dan dijamin oleh konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh negara. Dengan demikian, relasi antara kedaulatan rakyat dan hak konstitusional bersifat dialektis, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi pada saat yang sama mereka juga adalah subjek yang harus dilindungi oleh negara melalui jaminan konstitusional.
Septian Febriana, Firdaus, Kelas HTN, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
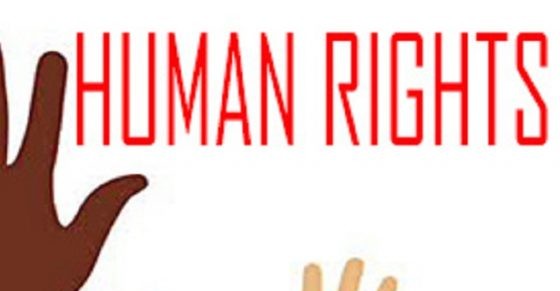
Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Hukum Tata Negara
Teori Kedaulatan Rakyat
Jean Jacques Rousseau dalam Du Contrat Social menekankan konsep volonté générale atau kehendak umum, di mana rakyat secara kolektif adalah pemegang kekuasaan tertinggi.[1] Rakyat menyerahkan sebagian kehendaknya untuk dikelola oleh negara demi kepentingan bersama, namun kedaulatan itu tetap tidak dapat dipindahtangankan.
John Locke, melalui Two Treatises of Government, menyatakan bahwa kekuasaan negara lahir dari kontrak sosial antara rakyat dan penguasa.[2] Apabila penguasa melanggar kontrak tersebut, rakyat berhak untuk menuntut atau bahkan mengganti penguasa. Konsep ini menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan demi menjamin kebebasan individu.
Montesquieu mengembangkan konsep trias politica, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[3] Teori ini dimaksudkan untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berpotensi menindas rakyat.
Hans Kelsen kemudian menawarkan teori hukum murni dengan konsep grundnorm atau norma dasar. Menurutnya, legitimasi kekuasaan negara bergantung pada keberlakuan norma dasar yang diterima oleh masyarakat.[4] Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui hukum yang berlaku dan ditaati secara umum.
Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Indonesia
Dalam UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan secara eksplisit. Pasal 1 ayat (2) menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, namun pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat di Indonesia bukanlah kedaulatan yang absolut, melainkan kedaulatan yang konstitusional.[5]
Hak Konstitusional Warga Negara
Definisi dan Karakteristik
Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi suatu negara. Hak ini memiliki karakteristik:
- Bersifat fundamental karena melekat pada martabat manusia.
- Dijamin secara hukum tertinggi, yaitu konstitusi.
- Berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara.
- Tidak dapat dihapuskan kecuali melalui mekanisme konstitusional.
Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hak konstitusional tidak hanya sebatas deklarasi, melainkan juga merupakan jaminan yang memiliki kekuatan mengikat terhadap semua lembaga negara.[6] Dengan demikian, keberadaan hak konstitusional merupakan syarat utama bagi berfungsinya prinsip negara hukum (rechsstaat).
Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa lembaga-lembaga negara didirikan tidaklain tidak bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dan menggapai tujuan negara. Dalam pembukaan undang-undang dasar negera republik Indonesia tertulis bahwasanya tujuan negara indoensia itu berupa (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadian sosial.
Hak Konstitusional dalam UUD 1945
UUD 1945 pasca amandemen memuat jaminan yang luas terhadap hak-hak warga negara, terutama dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J).[7] Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hingga hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.[8]
Selain itu, UUD 1945 juga memuat hak-hak khusus yang bersifat kolektif, seperti hak masyarakat adat untuk mempertahankan keberadaannya (Pasal 18B ayat (2)), serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)).[9] Dengan demikian, hak konstitusional bukan sekadar hak formal, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan negara hukum demokratis.
Hubungan Kedaulatan Rakyat dan Hak Konstitusional
Kedaulatan rakyat dan hak konstitusional memiliki hubungan timbal balik. Kedaulatan rakyat memberikan legitimasi bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, sedangkan hak konstitusional memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan.
Dalam negara hukum demokratis, kedaulatan rakyat tanpa perlindungan hak akan melahirkan tirani mayoritas.[10] Sebaliknya, perlindungan hak tanpa mekanisme kedaulatan rakyat akan melahirkan negara otoriter. Oleh karena itu, demokrasi konstitusional menjadi bentuk ideal, di mana kekuasaan rakyat dijalankan dalam batasan hukum yang menjamin hak-hak warga negara.
Menurut Bagir Manan, esensi demokrasi konstitusional terletak pada kemampuan konstitusi membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak rakyat.[11] Dengan kata lain, demokrasi konstitusional adalah pertemuan ideal antara kedaulatan rakyat dan hak konstitusional.
Penutup
Kedaulatan rakyat dan hak konstitusional merupakan dua konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedaulatan rakyat menegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi, sementara hak konstitusional menjamin bahwa setiap individu memiliki perlindungan atas hak-haknya dari potensi kesewenang-wenangan negara.
Dalam praktiknya, implementasi kedua konsep ini masih menghadapi tantangan, baik secara normatif, struktural, sosial-politik, maupun yudisial. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi melalui strategi penguatan yang mencakup penguatan konstitusionalisme, reformasi politik, peningkatan independensi lembaga demokrasi, pendidikan konstitusional, dan penegakan hukum yang konsisten.
Hanya dengan langkah-langkah tersebut, kedaulatan rakyat dapat diwujudkan secara substantif, dan hak konstitusional warga negara dapat benar-benar terlindungi. Dengan demikian, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, dapat tercapai.
Daftar Pustaka
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Bagir Manan. Teori dan Politik Konstitusi. Jakarta: FH UII Press, 2003.
Kelsen, Hans. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media, 2006.
Locke, John. Two Treatises of Government (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Montesquieu, The Spirit of Laws (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Rousseau, Jean Jacques. The Social Contract. New York: Cosimo Classics, 2007.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Bab XA tentang Hak Asasi Manusia..
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[1] Jean Jacques Rousseau, The Social Contract (New York: Cosimo Classics, 2007), hlm. 24.
[2] John Locke, Two Treatises of Government (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 119.
[3] Montesquieu, The Spirit of Laws (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 157.
[4] Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm. 49.
[5] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 71.
[6] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 91.
[7] UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.
[8] UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
[9] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 122.
[10] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 112.
[11] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Jakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 68.