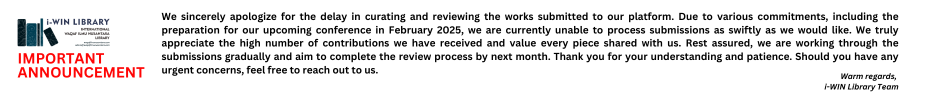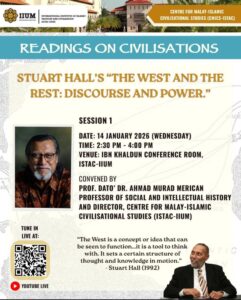Membedah Penerapan Green Claim Directive Sebagai Upaya Pengaburan Praktik Greenwashing di Indonesia

Di Indonesia, klaim-klaim lingkungan tumbuh jauh lebih cepat daripada mekanisme pengawasannya. Setiap tahun, semakin banyak produk yang dipasarkan dengan istilah “ramah lingkungan”, namun sebagian besar klaim tersebut tidak pernah melewati proses pembuktian yang memadai. Konsumen hanya menerima label dan narasi visual sebagai kebenaran, sementara perusahaan tetap bebas memproduksi citra hijau tanpa tanggung jawab substantif.[1] Pada titik inilah greenwashing berkembang: perusahaan menggunakan bahasa keberlanjutan untuk menutupi dampak ekologis mereka, bukan untuk menguranginya. Celah inilah yang menciptakan pasar yang penuh ilusi hijau, di mana penampilan lebih kuat daripada bukti.
Masalahnya tidak berhenti pada dimensi etika bisnis. Dalam perspektif hukum, Indonesia masih beroperasi dalam rezim yang hanya mampu menindak klaim menyesatkan setelah kerugian terjadi. UU Perlindungan Konsumen, UU Lingkungan Hidup, dan berbagai aturan sektoral memang melarang informasi palsu, tetapi tidak menyediakan mekanisme verifikasi ilmiah sebelum klaim dipublikasikan.[2] Dengan kata lain, hukum kita bekerja reaktif, bukan preventif. Tanpa standar baku untuk mengukur klaim hijau, tanpa metode wajib seperti analisis siklus hidup, dan tanpa lembaga verifikator independen.
Dalam dunia yang bergerak menuju ekonomi rendah karbon, kekosongan regulatif ini berbahaya. Ia bukan hanya menipu konsumen, tetapi juga menyesatkan arah kebijakan publik, melemahkan kredibilitas usaha mikro dan menengah yang benar-benar berupaya berkelanjutan, dan menciptakan kompetisi usaha yang tidak adil. Lebih jauh lagi, greenwashing justru melemahkan gerakan keberlanjutan itu sendiri yang dapat mengakibatkan degradasi kepercayaan publik terhadap agenda lingkungan.[3]
Di tengah problem tersebut, Green Claims Directive dari Uni Eropa menawarkan model yang berbeda, yaitu regulasi yang mewajibkan substansiasi ilmiah atas setiap klaim lingkungan, verifikasi pihak ketiga sebelum klaim disampaikan ke konsumen, serta transparansi penuh mengenai metodologi dan bukti.[4] Skema ini menggeser orientasi hukum dari sekadar melarang kebohongan menjadi memastikan kebenaran. Dalam konteks Indonesia, model seperti ini membuka pertanyaan penting, apakah rezim anti–greenwashing yang lebih struktural, transparan, dan berbasis bukti dapat diadaptasi untuk memperbaiki ketidakseimbangan antara klaim lingkungan dan kenyataan ekologis di pasar domestik.
Pembahasan dapat dimulai dengan menelusuri terlebih dahulu bagaimana Green Claims Directive dibangun atas kerangka filosofis bahwa informasi lingkungan merupakan hak konsumen sekaligus instrumen pengendalian pasar.[5] GCD menempatkan klaim lingkungan sebagai bentuk credence claim jenis informasi yang tidak dapat diverifikasi langsung oleh konsumen—sehingga negara harus memastikan adanya mekanisme pembuktian yang ketat sebelum klaim tersebut dipublikasikan. Dengan cara inilah Uni Eropa berusaha memutus rantai manipulasi yang kerap dilakukan melalui istilah ambigu seperti “eco-friendly”, “bio-based”, atau “carbon neutral” tanpa dasar ilmiah yang mencukupi. GCD mewajibkan setiap klaim untuk disertai bukti ilmiah, metodologi penilaian standar, pengujian pihak ketiga (third-party verification), serta pelaporan yang mudah diakses publik. Kehadiran sistem tersebut pada dasarnya mengubah klaim lingkungan dari sekadar alat pemasaran menjadi komponen akuntabilitas yang dapat diuji.
Ketika model seperti itu dipetakan ke keadaan Indonesia, muncul ketegangan yang menarik dalam lanskap regulatif. Secara normatif, Indonesia memang telah mengakui hak konsumen atas informasi yang benar dan tidak menyesatkan, sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen. UU Lingkungan Hidup pun mewajibkan setiap pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas dampak ekologisnya. Namun kedua kerangka hukum tersebut tidak membahas secara rinci bagaimana klaim lingkungan harus diverifikasi, disampaikan, dan diawasi. Ketiadaan aturan teknis membuat ruang interpretasi menjadi terlalu luas. Sebagian pelaku usaha menggunakan label hijau berdasarkan standar internal tanpa acuan ilmiah, sementara sebagian lainnya bergantung pada sertifikasi sukarela yang tidak selalu mengikuti metodologi yang seragam. Akibatnya, muncul lapisan regulatory gap yang membuka peluang terjadinya greenwashing secara sistemik, baik pada produk konsumsi sehari-hari maupun industri besar seperti energi, agrikultur, dan manufaktur.[6]
Dalam kondisi tersebut, prinsip-prinsip GCD menawarkan lensa untuk melihat apa saja yang sebenarnya hilang dari mekanisme domestik. Salah satu aspek penting adalah tuntutan transparansi metodologi yang digunakan untuk membuktikan klaim. Di Indonesia, belum ada standar baku yang menentukan metodologi penilaian lingkungan untuk setiap jenis klaimapakah terkait jejak karbon, penggunaan energi terbarukan, kemampuan daur ulang, atau kandungan bahan ramah lingkungan. Ketidakhadiran standar menimbulkan situasi di mana dua pelaku usaha dapat menggunakan istilah yang sama untuk dampak yang sangat berbeda. Model GCD, jika diadaptasi, dapat menjadi rujukan bagaimana negara menata kewajiban metodologis ini melalui life-cycle assessment, verifikasi independen, dan pelaporan berbasis traceability.
Selain itu, aspek pengawasan dan sanksi juga perlu diperhatikan. Uni Eropa secara jelas menempatkan otoritas sebagai penjaga integritas pasar, dengan memberikan kewenangan untuk menahan produk, menghapus klaim, hingga menjatuhkan denda yang proporsional.[7] Di Indonesia, lembaga seperti BPKN, Kementerian Perdagangan, dan OJK sebenarnya memiliki potensi besar untuk memainkan peran serupa, tetapi koordinasinya masih lemah dan tidak diarahkan secara khusus untuk menangani klaim lingkungan. Dengan memasukkan prinsip GCD, penguatan kelembagaan dapat diarahkan pada pembentukan satuan tugas khusus yang menangani informasi lingkungan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan konsisten.
Pembahasan juga perlu menggarisbawahi bahwa adaptasi konsep GCD tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas ekonomi Indonesia. Banyak usaha kecil dan menengah yang belum memiliki kapasitas untuk memenuhi standar verifikasi tinggi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana regulasi dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks ini, pengalaman Eropa menunjukkan pentingnya phased regulation atau penerapan bertahap, serta dukungan teknis untuk usaha kecil agar tidak terdepak dari pasar. Dengan cara itu, upaya memberantas greenwashing tidak berubah menjadi hambatan perdagangan yang bersifat disfungsional.[8]
Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa Green Claims Directive tidak sekadar menawarkan model regulasi baru, melainkan membuka ruang refleksi untuk melihat kelemahan-kelemahan struktural dalam hukum Indonesia. Ia menegaskan bahwa membiarkan klaim lingkungan tanpa verifikasi berarti membiarkan pasar berjalan dalam ilusi, merugikan konsumen, dan menghambat transisi ekologis yang seharusnya menjadi agenda nasional. Dengan melakukan pembacaan kritis terhadap GCD dan kondisi domestik, Indonesia memiliki peluang untuk merumuskan kerangka pengawasan klaim lingkungan yang lebih kuat, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan sosial-ekologisnya sendiri.
Penutup dari pembahasan ini pada akhirnya menegaskan bahwa Green Claims Directive bukan hanya sebuah instrumen regulasi Uni Eropa, melainkan sebuah paradigma baru yang memaksa setiap negara untuk meninjau ulang cara mereka memperlakukan informasi lingkungan dalam pasar. Pengalaman Eropa memperlihatkan bahwa klaim hijau tidak boleh dibiarkan menjadi ruang bebas di mana pelaku usaha dapat menyusun narasinya sendiri tanpa bobot bukti yang memadai. Ketika klaim lingkungan dibiarkan mengambang, pasar kehilangan integritasnya, konsumen kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan yang sadar, dan agenda keberlanjutan kehilangan pijakan etisnya. Dalam konteks tersebut, GCD memberi teladan bahwa keberlanjutan membutuhkan lebih dari niat baik; ia membutuhkan struktur hukum yang mampu memastikan bahwa setiap klaim, sekecil apa pun, dapat diuji dan diverifikasi.
Bagi Indonesia, relevansi gagasan ini semakin kuat karena kompleksitas pasar domestik dan tingginya kerentanan konsumen terhadap informasi yang menyesatkan. Di tengah maraknya sertifikasi sukarela, iklan hijau yang berlebihan, dan penggunaan istilah ramah lingkungan tanpa standar jelas, hadirnya regulasi berbasis prinsip GCD dapat menjadi langkah penting untuk membangun rejim kejujuran ekologis. Adaptasi konsep ini tidak berarti menyalin seluruh rancangan Eropa, melainkan memetakannya ke kebutuhan lokal, kondisi industri, serta kapasitas lembaga negara. Justru di situlah peluang pembaruan hukum berada pada kemampuan untuk menjahit prinsip global ke dalam struktur nasional dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan kepatuhan pelaku usaha.
Akhirnya, pemberantasan greenwashing bukan sekadar upaya teknis, melainkan upaya etis untuk menempatkan keberlanjutan sebagai sebuah kebenaran yang dapat dibuktikan, bukan sekadar janji yang diklaim. Dengan menjadikan Green Claims Directive sebagai referensi konseptual, Indonesia memiliki kesempatan untuk menata ulang tata kelola klaim lingkungan secara lebih tegas, transparan, dan akuntabel. Jika dilakukan dengan konsisten, langkah tersebut bukan hanya akan melindungi konsumen, tetapi juga memperkuat fondasi moral dan hukum bagi transformasi hijau yang benar-benar substansial. Dalam lanskap regulasi yang terus berkembang, komitmen terhadap kejujuran lingkungan inilah yang menjadi penanda bahwa perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan tidak hanya retoris, tetapi benar-benar dijalankan dalam praktik.
[1] Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, and Agus Suwandono, “Consumer Protection Against False Ecolabel Claims : A Legal Analysis in Indonesia JURNAL” 2, no. 2 (2024): 200–208.
[2] Ignacio Carreño, “To Address ‘ Greenwashing ’ and Misleading Environmental Claims , the European Commission Publishes a Proposal on ‘ Green Claims ’ and Their Substantiation,” no. April (2023): 607–11, https://doi.org/10.1017/err.2023.36.
[3] Romansyah Fitra Lebie, Rio Riccha, and Br Sihombing, “Greenwashing as Environmental Fraud : Highlighting the Lack of Regulation and Law Enforcement in Indonesia” 7, no. 2 (2025): 532–44.
[4] Zico Junius Fernando and Ahmad Wali, “Greenwashing as a Crime and the Urgency of Redesigning the Environmental Criminal Law Paradigm,” no. June (2025): 55–90.
[5] European Parliament. Report on the Proposal on the Substantiation and Communication of Explicit Environmental Claims (Green Claims Directive). A9-0056/2024. 2024.
[6] Sandulli, Marco, and Maureen O’Hare. Greenwashing and Environmental Claims in European and International Regulation: A Proposal for a Green Claims Directive. 2022.
[7] Pangloly, Deslyana Rante, et al. “Pengaturan Hukum Lingkungan terhadap Praktik Greenwashing di Indonesia.” Lex Administratum 10, no. 2 (2022): 1–12.
[8] Lyon, Thomas P., and Magali A. Delmas. “Greenwashing: Corporate Environmental Disclosure under Threat of Audit.” Journal of Economics & Management Strategy 27, no. 3 (2018): 599–620.