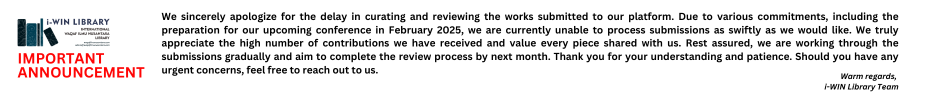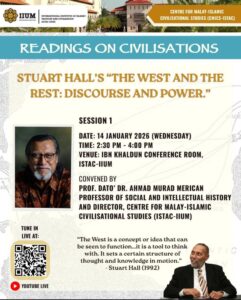PERLU UU KEADILAN IKLIM: MELAWAN KRISIS PLANET TRIPLE-PLANETARY CRISIS

PENDAHULUAN
Kesehatan planet bumi saat ini menghadapi ancaman simultan yang dikenal sebagai Triple-Planetary Crisis (TPC). Terminologi yang diserukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini merujuk pada tiga dimensi krisis yang saling memperkuat: perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis ini tidak dapat ditangani secara terpisah. Diperlukan kolaborasi dan kerja sama yang terintegrasi dari pemerintah, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil untuk menghadapinya. Earth Commission bahkan telah mengusulkan perlunya peningkatan skala piranti Safe and Just Planetary Boundaries, menyimpulkan bahwa batas aman saja tidaklah cukup tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan.
Bagi Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, TPC bukan lagi ancaman hipotetis melainkan realitas eksistensial. Manifestasi krisis iklim telah terkonfirmasi melalui data terbaru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan kenaikan suhu rata-rata nasional dapat melampaui 1,3°C pada periode 2020–2049, diperkuat oleh tren suhu tinggi ekstrem yang terjadi pada 2023–2025. Selain itu, Indonesia menghadapi peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan periode kering berkepanjangan. Di dimensi biodiversitas, laju deforestasi tetap menjadi isu signifikan, dengan total dugaan deforestasi pada tahun 2024 mencapai luas 297.950 hektar. Sementara itu, krisis polusi tercermin dari isu kualitas udara kronis, di mana pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, khususnya yang beroperasi di dekat Jakarta, diidentifikasi sebagai penyumbang utama yang memerlukan kebijakan no regrets.
Analisis terhadap penanganan TPC di Indonesia menunjukkan adanya problem mendasar: kegagalan regulasi yang terfragmentasi. Kerangka hukum yang ada cenderung memisahkan penanganan masing-masing krisis, misalnya, upaya mitigasi iklim diatur dalam komitmen Nationally Determined Contribution (NDC), sementara polusi diatur melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan konservasi diatur dalam UU sektoral terkait. Pendekatan yang sektoral ini menciptakan celah regulasi (regulatory arbitrage) dan inefisiensi dalam penegakan hukum, sehingga respons yang dilakukan hanya bersifat tambal sulam dan gagal mengatasi akar permasalahan TPC secara holistik. Untuk mencapai stabilitas dan keberlanjutan bumi, diperlukan arsitektur hukum baru yang mengintegrasikan ketiga pilar krisis ini di bawah satu payung keadilan yang mengikat.
Keadilan iklim (Climate Justice) merupakan prasyarat mutlak dalam menghadapi krisis iklim dan ekologi dalam tatanan politik yang demokratis yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia (HAM). Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian fundamental dari HAM. Dengan demikian, isu iklim adalah masalah hak konstitusional.
Konsep keadilan iklim mencakup empat prinsip utama: keadilan rekognisi (pengakuan hak dan kearifan), keadilan prosedural (hak partisipasi dan bersuara), keadilan distributif (distribusi beban dan manfaat yang adil, di mana pihak yang lebih rentan harus mendapatkan keadilan yang lebih banyak), serta institusi yang kuat namun fleksibel. Kelompok masyarakat yang rentan, seperti nelayan tradisional dan masyarakat adat, adalah pihak yang paling menderita akibat TPC, sehingga harus menjadi sentra utama dalam perumusan kebijakan adaptasi.
Sayangnya, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi payung setingkat Undang-Undang (UU) yang secara komprehensif dan mengikat mengatur pengendalian perubahan iklim dan memasukkan prinsip keadilan iklim secara eksplisit. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan, ketiadaan regulasi payung yang mengikat multi-sektor mengakibatkan komitmen iklim (seperti NDC) hanya berada di level kebijakan, yang rentan terhadap perubahan rezim atau kepentingan politik.
Kegagalan legislatif untuk membuat UU Keadilan Iklim (UU KI) yang komprehensif dapat ditafsirkan sebagai kelalaian negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak generasi mendatang (intergenerational equity). Hak-hak fundamental ini, seperti hak atas kesehatan dan kebebasan, tidak dapat dipenuhi dengan kondisi ekologis yang semakin memburuk. Oleh karena itu, UU KI harus berfungsi sebagai instrumen untuk mengikat negara pada pertanggungjawaban intergenerasi ini. Diperlukan akomodasi eksplisit terhadap asas non-regresi, bahwa standar perlindungan lingkungan tidak boleh surut, dan asas tanggung jawab bersama yang dibedakan. Masuknya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 menjadi momentum penting yang harus dimanfaatkan untuk menghadirkan keadilan iklim melalui instrumen hukum tertinggi.
PEMBAHASAN
Merekonstruksi Akuntabilitas Korporasi dan Menghapus Impunitas Ekologis
Keadilan iklim tidak akan tercapai tanpa adanya akuntabilitas tegas terhadap para pelaku kerusakan lingkungan berskala besar. Realitas penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketidakadilan distributif yang sistemik, di mana beban krisis dipikul oleh masyarakat rentan sementara penyebab utama seringkali menikmati impunitas.
1. Akar Ketidakadilan Distributif: Represi Rakyat, Permisifitas Korporasi
Krisis iklim telah meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi di Indonesia. Misalnya, kehidupan nelayan tradisional semakin dipersulit karena perubahan iklim memengaruhi hasil tangkapan dan pola cuaca ekstrem. Namun, ketika kerentanan ini terjadi, sistem hukum seringkali gagal memberikan perlindungan yang setara (equal protection before the law).
Fenomena yang disebut sebagai impunitas ekologis sangat mencolok dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Terdapat ketimpangan mencolok di mana aparat penegak hukum bersikap represif terhadap masyarakat, seperti penangkapan petani lokal atas dugaan membakar lahan seluas satu hektar, namun bersikap permisif terhadap korporasi besar. Beberapa korporasi yang konsesinya mengalami kebakaran luasnya mencapai puluhan ribu hektar seringkali tidak dikenai tindakan hukum pidana maupun administratif yang setara. Pola ini terus berulang, di mana kebakaran terjadi di wilayah yang sama, milik korporasi yang sama, tanpa penindakan serius, menunjukkan adanya kegagalan struktural negara dalam pengawasan.
Ketidaktegasan ini memperdalam ketidakadilan ekologis, di mana beban penderitaan dipikul oleh kelompok yang paling rentan. Secara yuridis, ketimpangan tersebut menegaskan lemahnya implementasi asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability), yang seharusnya dirancang untuk menanggulangi kerusakan lingkungan oleh korporasi besar dengan kekuatan modal kuat. Kegagalan dalam menindak pelaku utama menciptakan efek jera yang lemah, membuka ruang bagi impunitas, dan mendorong moral hazard dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengadilan memegang peran sentral dalam menegaskan kembali prinsip strict liability dan precautionary principle untuk memastikan korporasi tidak kebal dari akuntabilitas.
Apabila impunitas korporasi (khususnya kegagalan menindak tegas pelanggaran lingkungan berulang) terus berlanjut, praktik bisnis ekstraktif yang merusak akan tetap menguntungkan. Hal ini secara langsung mendorong percepatan deforestasi (krisis keanekaragaman hayati) dan peningkatan emisi (krisis iklim), menjadikan celah hukum yang permisif ini sebagai faktor akselerasi utama TPC di Indonesia. UU KI harus dirancang untuk menutup celah impunitas ini secara permanen.
2. Pilar Hukum untuk Akuntabilitas Korporasi dalam UU KI
UU Keadilan Iklim harus menjadi instrumen untuk merekonstruksi akuntabilitas dengan tiga pilar utama:
a. Kewajiban Uji Tuntas Iklim (Mandatory Climate Due Diligence – MCDD):
UU KI harus mewajibkan korporasi untuk melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap dampak iklim dan hak asasi manusia (mHRDD) sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Kewajiban ini harus mencakup identifikasi, pencegahan, dan mitigasi risiko yang terkait dengan emisi gas rumah kaca dan kerusakan lingkungan. Analisis menunjukkan bahwa mekanisme pasar karbon berisiko menjadi “pintu belakang” untuk bisnis ekstraktif dan greenwashing jika tidak ada pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, MCDD menjadi penting untuk memastikan perusahaan tidak hanya bersembunyi di balik mekanisme perdagangan emisi tetapi melakukan penurunan emisi mendasar.
b. Penguatan Litigasi Iklim dan Perlindungan Hukum:
Pengadilan memiliki peran penting dalam mendorong climate litigation. UU KI perlu memfasilitasi gerakan litigasi iklim, yang dikenal sebagai The Second Wave of Climate Litigation. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat payung hukum bagi Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit atau Actio Popularis) dalam kasus perubahan iklim, mengatasi permasalahan doktrinal seperti hak gugat dan pembuktian kausalitas. Gugatan warga negara telah terbukti menjadi instrumen penting untuk menuntut negara atas kebijakan yang melanggar hak lingkungan, seperti kasus perizinan pertambangan batu bara di Samarinda. Selain itu, UU KI harus memberikan perlindungan hukum berupa instrumen Anti-SLAPP yang progresif dan bertujuan melindungi aktivis lingkungan, peneliti, dan media dari kriminalisasi yang berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional.
c. Mekanisme Ganti Rugi Iklim yang Komprehensif:
UU KI harus menetapkan mekanisme ganti rugi yang tegas dan mencakup kompensasi atas kerugian sosial dan ekonomi yang diderita kelompok rentan akibat krisis iklim. Sumber-sumber dana iklim, termasuk yang berasal dari pasar karbon, tidak boleh dilihat hanya sebagai devisa baru, melainkan harus diarahkan untuk mendukung aksi-aksi iklim inisiatif masyarakat dan meningkatkan daya lenting kelompok rentan.
Memperkuat Keadilan Prosedural dan Rekognisi sebagai Fondasi Ketahanan Iklim Nasional
Fondasi ketahanan iklim nasional harus dibangun di atas pengakuan hak dan partisipasi inklusif, terutama bagi komunitas yang secara historis terpinggirkan. Keadilan prosedural dan rekognisi merupakan dua pilar utama yang memastikan adaptasi yang dilakukan efektif dan mencegah maladaptasi.
1. Mewujudkan Keadilan Prosedural: Partisipasi Bermakna dan Hak untuk Bersuara
Keadilan prosedural menuntut bahwa proses pengambilan keputusan harus inklusif dan partisipatif, di mana kelompok rentan memiliki prosedur yang memungkinkan mereka bersuara dan menyajikan solusi. RUU KI harus mewajibkan pengembangan kebijakan dan aksi mitigasi iklim, termasuk penyusunan dokumen komitmen iklim (NDC/SNDC), agar transparan, kolaboratif, dan mencantumkan inisiatif masyarakat di level tapak.
Keadilan prosedural menjamin bahwa agency (kemampuan bertindak) dari kelompok rentan diakui. Ketika kelompok marginal dan masyarakat adat tidak dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan adaptasi dan mitigasi, kebijakan yang dihasilkan berisiko menjadi aksi yang gagal atau bahkan memperburuk kerentanan yang sudah ada (maladaptasi). Oleh karena itu, mandat partisipasi eksplisit dalam UU KI adalah prasyarat fungsional bagi keberhasilan adaptasi nasional. Koalisi Masyarakat Sipil, termasuk WALHI dan ICEL, telah mendesak agar proses pembentukan UU KI sendiri harus transparan, partisipatif, dan inklusif.
Penguatan instrumen hukum seperti Gugatan Warga Negara (Actio Popularis) juga berperan penting dalam keadilan prosedural. Mekanisme ini memungkinkan warga negara membela kepentingan umum dan mengajukan gugatan terhadap pemerintah yang kebijakannya dianggap melanggar hak lingkungan dan memperburuk krisis iklim, seperti kasus yang diajukan terhadap pemerintah kota Samarinda terkait perizinan pertambangan batu bara yang berlebihan. UU KI harus menghilangkan ambiguitas hukum yang menghambat litigasi rakyat ini.
2. Keadilan Rekognisi: Pengakuan Hak Masyarakat Adat sebagai Aksi Iklim
Keadilan rekognisi berfokus pada pengakuan hak, budaya, dan kearifan lokal. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) diakui secara global dan domestik sebagai role model ketahanan iklim. Mereka memiliki pengetahuan tradisional dan praktik pengelolaan berkelanjutan, seperti agroforestri, reboisasi, dan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal, yang berkontribusi besar terhadap ketahanan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon.
Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat bukanlah sekadar masalah identitas, melainkan strategi krusial untuk melindungi ekosistem dari TPC. UU KI harus memberikan mandat hukum untuk menerjemahkan kearifan lokal ini menjadi kebijakan publik yang mengikat. Dengan adanya pengakuan hukum, wilayah kelola rakyat dan hutan adat akan menjadi fondasi bagi wilayah kehidupan masyarakat dan penjaga ekosistem.
Pengakuan hak MAKL menghasilkan sinergi antara konservasi dan kesejahteraan. Melindungi MAKL secara simultan membantu menyelesaikan dua komponen TPC (iklim dan biodiversitas) sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal, seperti yang terlihat dari potensi keuntungan bagi komunitas adat dari proyek energi terbarukan. Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen penguatan peran MAKL dan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat di forum internasional (COP30). UU KI harus mengikat komitmen ini di tingkat domestik, terutama memastikan adanya mekanisme pembagian manfaat yang adil dari pendanaan iklim yang diperoleh negara.
KESIMPULAN
Krisis Planet Triple-Planetary Crisis, yang melibatkan perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, mengharuskan Indonesia untuk merombak arsitektur hukumnya. Analisis menunjukkan bahwa respons hukum yang terfragmentasi saat ini tidak memadai dan diperparah oleh kegagalan struktural dalam penegakan hukum, yang ditandai dengan impunitas ekologis korporasi dan ketidakadilan distributif. Sistem hukum yang represif terhadap masyarakat lokal namun permisif terhadap korporasi besar menciptakan moral hazard dan mempercepat laju TPC.
Undang-Undang Keadilan Iklim (UU KI) merupakan kebutuhan legislatif yang mendesak dan keharusan konstitusional untuk melindungi hak-hak lingkungan hidup generasi kini dan mendatang. UU KI harus berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat multi-sektor, menjamin implementasi asas non-regresi, dan secara eksplisit menguatkan keempat pilar keadilan iklim: distributif, prosedural, rekognisi, dan institusional. Dengan instrumen hukum yang kuat ini, Indonesia dapat beralih dari sekadar menjadi pedagang krisis iklim (mengandalkan kredit karbon dan teknologi) menuju penegakan penurunan emisi mendasar dan rekonsiliasi keadilan ekologis dan sosial, memastikan tercapainya masyarakat yang beradaptasi dan berkeadilan.
DAFTAR RUJUKAN
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri. (2025). 2025: Tahun terpanas kedua dalam sejarah dan dampaknya bagi Indonesia serta Sulawesi Tengah. GAW-Bariri.bmkg.go.id. https://gaw-bariri.bmkg.go.id/index.php/karya-tulis-dan-artikel/artikel/364-2025-tahun-terpanas-kedua-dalam-sejarah-dan-dampaknya-bagi-indonesia-serta-sulawesi-tengah
Hasan, K., & Swastika, A. B. (2025). Indonesia air quality 2024: As Jakarta’s metro areas all break WHO limit up to tenfold, government opts for ‘wait-and-see’. Centre for Research on Energy and Clean Air. https://energyandcleanair.org/publication/indonesia-air-quality-2024/
Hasjanah, K. (2022). Memahami keadilan iklim dalam aksi iklim global dan penerapannya di Indonesia. Institute for Essential Services Reform (IESR). https://iesr.or.id/memahami-keadilan-iklim-dalam-aksi-iklim-global-dan-penerapannya-di-indonesia/
Institute for Essential Services Reform (IESR). (2023). Menuju COP-28: Indonesia perlu menyuarakan aksi nyata dalam mengatasi krisis iklim. IESR. https://iesr.or.id/menuju-cop-28-indonesia-perlu-menyuarakan-aksi-nyata-dalam-mengatasi-krisis-iklim/
Kementerian Kehutanan. (2025). Komitmen 1,4 juta hektare hutan adat diumumkan Indonesia pada forum LCIPP COP30. Kehutanan.go.id. https://www.kehutanan.go.id/news/komitmen-1-4-juta-hektare-hutan-adat-diumumkan-indonesia-pada-forum-lcipp-cop-30
Koalisi Keadilan Iklim. (t.t.). Kertas posisi koalisi keadilan iklim mendesak negara segera menyusun UU keadilan iklim [Kertas Posisi].
Manurung, T., Sukmara, D., & Younastya, A. (2024). Status Deforestasi Indonesia 2024. Simontini. https://simontini.id/id/status-deforestasi-indonesia-2024
Sabillah, A., & Fitriani, N. F. (2025). Tanggung jawab korporasi di balik kebakaran hutan dan lahan [Amicus Curiae untuk Perkara No: 250/Pdt.G/LH/2024/PN.Plg]. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Satriya, C. A. (2025). Triple-Planetary Crisis dan Apa Komitmen Kita?. MariNews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/triple-planetary-crisis-dan-apa-komitmen-kita-04n
Sembiring, Z. A., & Baihaqie, A. G. (2020). Litigasi perubahan iklim privat di Indonesia: Prospek dan permasalahannya. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 7(1), 118–140. https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.215
Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup layak: Kajian hukum tata negara terhadap tanggung jawab negara dalam pembangunan berkelanjutan. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(3), 175–186. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5767
Syaharani, D., Shafira, D., & Widyaningsih, G. A. (2023). Mengapa Indonesia harus memiliki Undang-Undang perubahan iklim? (Policy and Legal Update). Indonesian Center for Environmental Law.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2025). Karhutla dan impunitas: Negara terus lindungi korporasi pembakar hutan dan lahan. WALHI. https://www.walhi.or.id/karhutla-dan-impunitas-negara-terus-lindungi-korporasi-pembakar-hutan-dan-lahan-wahana-lingkungan-hidup-indonesia-walhi
Wahyuni, S. (2025). Krisis iklim makin persulit kehidupan nelayan tradisional. Mongabay.co.id. https://mongabay.co.id/2025/07/14/krisis-iklim-makin-persulit-kehidupan-nelayan-tradisional/
Yappika Actionaid. (2023). Indonesia memerlukan UU keadilan iklim. Yappika Actionaid. https://yappika-actionaid.or.id/en/liputan-media/read/indonesia-memerlukan-uu-keadilan-iklim