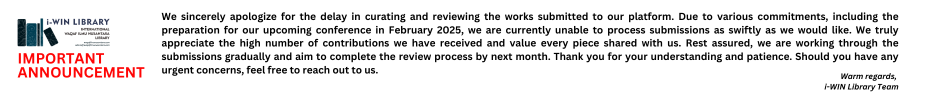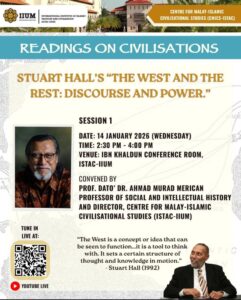Banjir di Sumatra Utara Ketika Hulu Rusak Hilir Menanggung

Banjir yang melanda beberapa wilayah Sumatra Utara baru-baru ini bukan sekadar peristiwa alam yang dating tiba-tiba tanpa peringatan. Banjir tersebut menyisakan tanda tanya besar tentang bagaimana kondisi lingkungan kita sebenarnya. Curah hujan memang tinggi, tetapi hujan bukan satu-satunya penyebab. Jika ekosistem di hulu masih sehat, jika hutan masih berfungsi sebagai penyerap air, dan jika sungai masih memiliki ruang untuk mengalir sebagaimana mestinya, bencana sebesar ini semestinya tidak akan terjadi. Banjir ini justru seperti cermin yang memantulkan wajah sebenarnya bagaimana pengelolaan lingkungan kita yang masih penuh celah.
Pembahasan dimulai dari banyak daerah, warga menyampaikan bahwa air datang sangat cepat, lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena seperti ini menunjukkan adanya perubahan pola aliran air. Ketika daerah hulu kehilangan vegetasi penahan, air hujan tidak lagi meresap ke tanah. Ia langsung mengalir deras, menyeret lumpur dan material lain seperti bongkahan kayu, lalu mempercepat terjadinya banjir bandang. Situasi seperti ini mengindikasikan adanya degradasi lingkungan yang sudah cukup parah. Masyarakat akhirnya mulai bertanya-tanya: dari mana asal kerusakan ini? Bagaimana mungkin air yang dulu mengalir tenang kini berubah menjadi ancaman yang mematikan?
Dugaan pun bermunculan. Masyarakat menyoroti pembukaan lahan di kawasan hulu, aktivitas pertambangan, hingga keberadaan PLTA atau aktivitas industri lain yang mungkin mempengaruhi stabilitas Daerah Aliran Sungai (DAS). Belum tentu semua dugaan itu benar. Namun fakta bahwa masyarakat mencurigai berbagai pihak menunjukkan bahwa informasi tentang pengelolaan lingkungan memang tidak pernah transparan. Dalam kondisi seperti ini, rasa percaya masyarakat pun menurun. Ketika masyarakat merasa tidak memiliki akses terhadap informasi, ruang bagi spekulasi pun membesar.
Kita tidak boleh mengabaikan bahwa persoalan lingkungan di Indonesia hampir selalu terkait dengan tata kelola izin yang lemah. Seringkali izin pembukaan lahan diberikan tanpa mempertimbangkan kondisi ekologis kawasan. Analisis dampak lingkungan dibuat sebagai syarat administratif, bukan alat analisis yang benar-benar menentukan boleh tidaknya suatu proyek berjalan. Padahal hukum lingkungan, melalui asas precautionary principle dan prevention, mengharuskan pemerintah mempertimbangkan risiko terlebih dahulu sebelum suatu izin dikeluarkan. Namun dalam praktiknya, prinsip ini sering sekadar menjadi kalimat indah di atas kertas.
Banjir ini juga memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah daerah mengelola ruang dengan perspektif ekologis. Banyak daerah yang menyerahkan pemanfaatan lahan kepada kepentingan investasi tanpa terlebih dahulu memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Padahal wilayah Sumatra Utara memiliki topografi yang sangat bergantung pada keseimbangan hulu–hilir. Rusaknya satu bagian saja dapat menimbulkan efek domino pada bagian lainnya. Ketika pemerintah tidak menjaga keseimbangan ini, masyarakatlah yang akhirnya harus menanggung akibatnya.
Di sisi lain, berbagai laporan lapangan menunjukkan bahwa banyak sungai mengalami pendangkalan karena sedimentasi berlebihan. Ketika sedimentasi meningkat, volume sungai berkurang dan daya tampungnya melemah. Inilah yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak banjir. Sedimentasi ini bukan muncul secara tiba-tiba; ia merupakan hasil dari proses panjang kerusakan hulu. Sayangnya, proses panjang itu jarang sekali menjadi bahan kajian serius. Banjir dianggap semata-mata akibat hujan, padahal akar masalahnya sudah bertumpuk selama bertahun-tahun.
Partisipasi masyarakat menjadi aspek yang sering terpinggirkan dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat yang tinggal dekat kawasan hulu sebenarnya memiliki banyak pengetahuan lokal tentang bagaimana menjaga keseimbangan alam. Mereka mengetahui titik-titik rawan longsor, daerah yang seharusnya tidak dibuka, dan batas-batas alam yang harus dihormati. Namun sayangnya, suara mereka jarang diikutsertakan dalam penyusunan AMDAL atau kebijakan lingkungan lainnya. Padahal hukum lingkungan Indonesia telah memberikan ruang bagi partisipasi publik sebagai salah satu pilar penting. Ketika pilar ini diabaikan, lahirlah kebijakan yang tidak benar-benar berpihak pada keselamatan lingkungan dan manusia.
Penulis memberi tanggapan mengenai masalah izin dan pengawasan, banjir ini juga mengungkap lemahnya penegakan hukum lingkungan. Banyak perusahaan atau pihak yang melanggar aturan namun hanya dikenai sanksi administratif ringan. Sementara sanksi pidana jarang diterapkan kecuali kasusnya sudah viral atau menimbulkan kerugian besar. Padahal UU PPLH sebenarnya telah memberikan landasan kuat untuk menjerat pelaku perusakan lingkungan dengan sanksi pidana. Namun hukum yang kuat tidak berarti apa-apa jika tidak ditegakkan secara konsisten. Akibatnya, pelanggaran terus terulang, kerusakan terus berlangsung, dan bencana terus menghantui.
Pemerintah daerah juga perlu melakukan reformasi dalam tata ruang. Banyak wilayah pemukiman dibangun terlalu dekat dengan bantaran sungai atau kawasan rawan banjir. Bahkan dalam beberapa kasus, izin pembangunan diberikan tanpa analisis risiko bencana yang memadai. Ketika banjir datang, masyarakat yang tinggal di kawasan ini tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan diri. Seharusnya kawasan bantaran sungai dijadikan ruang terbuka hijau dan buffer zone, bukan area pemukiman atau industri. Tetapi karena tata ruang seringkali disusun tanpa pendekatan ekologis, risiko bencana pun meningkat.
Satu hal lain yang jarang diperbincangkan adalah perubahan iklim. Curah hujan ekstrem yang terjadi belakangan ini memang tidak bisa dilepaskan dari dampak perubahan iklim global. Namun perubahan iklim hanya memperparah kondisi yang sudah rapuh. Jika lingkungan kita dalam keadaan sehat, dampak perubahan iklim tidak akan sebesar ini. Namun jika hutan sudah gundul, DAS rusak, dan tata ruang bermasalah, maka sedikit saja perubahan pola cuaca dapat memicu bencana besar.
Di tengah semua persoalan ini, masyarakat sesungguhnya hanya ingin satu hal: adanya kepastian bahwa bencana seperti ini tidak akan terus menjadi rutinitas tahunan. Mereka ingin pemerintah hadir bukan hanya saat bencana sudah terjadi, tetapi juga saat mencegahnya. Mereka ingin kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan, bukan sekadar menarik investasi tanpa aturan. Mereka ingin perusahaan yang bekerja di wilayah mereka bertanggung jawab, bukan justru memperparah kerusakan alam.
Pada akhirnya, banjir Sumatra Utara kali ini harus menjadi pembelajaran bersama. Ini bukan hanya soal air yang meluap, tetapi tentang sistem yang rusak. Tentang izin yang diberikan tanpa kajian serius. Tentang pengawasan yang longgar. Tentang hukum yang lemah. Tentang hulu yang diabaikan dan hilir yang menanggung akibatnya. Semua ini harus diubah jika kita ingin masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Penutup dari pembahasan ini banjir seharusnya menjadi titik tolak untuk membenahi tata kelola lingkungan secara menyeluruh. Pemerintah harus memperbaiki sistem perizinan, memperketat pengawasan, memperkuat penegakan hukum, serta melibatkan masyarakat secara aktif. Perusahaan harus menjalankan kewajiban lingkungan dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya mematuhi aturan di atas kertas. Dan kita semua, sebagai masyarakat, perlu menyadari bahwa lingkungan bukan warisan semata, tetapi amanah yang harus dijaga bersama.
Jika langkah-langkah ini tidak segera diambil, maka banjir serupa hanya tinggal menunggu waktu. Dan setiap kali air datang membawa lumpur dan batu dari hulu, kita akan kembali menyalahkan hujan, padahal kita sendiri yang mengabaikan tanda-tanda kerusakan jauh sebelum bencana itu terjadi.